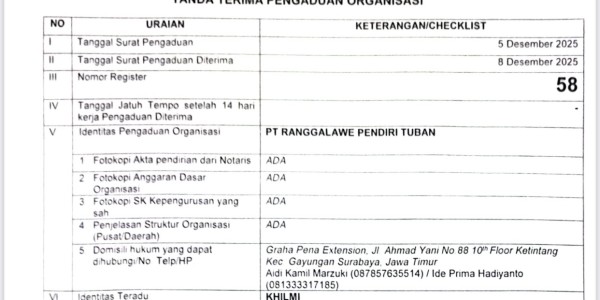telusur.co.id - Oleh : Denny JA
Dua kutipan dari dua sufi ini mengajak kita menyelam di kedalaman samudra batin.
“Agamaku adalah cinta. Setiap hati manusia adalah rumah ibadahku.”
- Jalaluddin Rumi (1207–1273)
Kutipan ini melampaui batas agama dan budaya, menjadi fondasi universal bagi kemanusiaan. Bagi Rumi, cinta bukan sekadar emosi, melainkan inti dari segala eksistensi.
Ia adalah jalan menuju sumber cahaya yang menyinari kegelapan, dan jembatan yang menyatukan perbedaan.
Di era ini, ketika dunia semakin terhubung oleh teknologi, kutipan Rumi menjadi relevan lebih dari sebelumnya. Kita hidup dalam zaman yang penuh kontradiksi: teknologi mendekatkan manusia secara fisik, tetapi menjauhkan mereka secara emosional.
Di tengah hiruk-pikuk data dan algoritma, hati manusia menjadi sunyi, potensial kehilangan koneksi dengan esensi cinta yang sejati.
Ini kutipan kedua :
“Ya Tuhan, jika aku memuja-Mu karena inginkan surga, tutuplah pintu surga bagiku. Jika aku memuja-Mu karena takut neraka, cemplungkanlah aku ke dalam neraka. Tapi jika aku memuja-Mu karena cintaku pada-Mu, jangan Kau tolak cintaku.”
- Rabiah Adawiyah (717–801)
Rabiah Adawiyah mengajarkan cinta tanpa syarat, cinta yang murni dan melampaui kepentingan pribadi.
Baginya, berorientasi pada keagungan adalah tujuan, bukan sarana untuk mendapatkan surga atau menghindari neraka. Cinta yang seperti ini adalah penyerahan total, sebuah jalan menuju kebebasan spiritual yang sejati.
Di era kini, pesan Rabiah mengingatkan kita untuk melampaui logika transaksional, baik dalam hubungan antarmanusia maupun dengan sesuatu yang lebih besar dibandingkan diri pribadi.
Ketika teknologi mendominasi kehidupan, kita sering terjebak dalam hubungan yang bersifat kalkulatif, apa yang bisa saya dapatkan dari ini?
Spirit Rabiah adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan melalui perhitungan, melainkan dalam ketulusan memberi dan menerima cinta.
Tapi kini kita hidup di era Artificial Intelligence. Ini sebuah realitas yang berbeda.
Para sufi hidup dalam zaman yang tenang, di mana perjalanan spiritual dilakukan melalui keheningan, refleksi, dan dialog batin. Tapi kini, kita berada di era Artificial Intelligence (AI), yang mengubah cara hidup manusia secara mendasar.
Era AI membawa banjir informasi tanpa henti. Sementara para sufi mencari kebijaksanaan dalam keheningan, kita sering kali kehilangan makna di tengah kebisingan data.
Hubungan manusia, yang dahulu penuh keintiman emosional, kini banyak bergantung pada media sosial dan algoritma. Ironisnya, meski teknologi menghubungkan miliaran manusia, rasa kesepian justru meningkat.
Kemajuan ekonomi dan melimpahnya hiburan digital juga menciptakan tekanan baru.
Data menunjukkan bahwa, kini mereka yang mati karena bunuh diri lebih banyak dibandingkan mereka yang mati karena terorisme ditambah perang ditambah bencana alam.
Para sufi menjalani kehidupan sederhana yang berfokus pada kebahagiaan batin, sementara kita hidup dalam dunia yang memuja produktivitas dan konsumsi.
Di era ini, pesan para sufi tentang cinta, kesederhanaan, dan refleksi menjadi semakin penting.
Buku kecil ini sebuah undangan untuk menyelam kedalaman diri. Ia terdiri dari 13 bab.
Dalam Bab 1, dieksplor isu Teknologi dan Tantangan Spiritualitas di Era AI. Teknologi telah membuka jalan baru menuju kemajuan, tetapi juga menimbulkan tantangan spiritual yang mendalam.
Di bab pertama, buku ini mengeksplorasi bagaimana AI telah mengubah cara manusia memahami eksistensi dan makna.
Media sosial, algoritma personalisasi, dan realitas virtual sering kali menciptakan ilusi makna yang dangkal, menjauhkan manusia dari hubungan yang sejati dengan sesama dan alam sekitar.
Namun, bab ini juga menyoroti potensi positif teknologi. AI dapat menjadi alat untuk mendalami spiritualitas, seperti melalui aplikasi meditasi, ruang virtual lintas iman, atau algoritma yang mendukung refleksi diri.
Pertanyaan inti yang diajukan adalah: apakah kita mengendalikan teknologi untuk mendukung perjalanan spiritual, atau apakah kita menjadi tawanan dari ilusi yang diciptakannya?
Dalam Bab 2-4, dibahas soal Sains dan Spiritualitas: Harmoni untuk Kesejahteraan. Bab ini menyelami hubungan antara spiritualitas dan sains, khususnya neuroscience dan psikologi positif.
Penelitian menunjukkan bahwa, praktik seperti meditasi, doa, dan refleksi tidak hanya meningkatkan kesehatan mental, tetapi juga memperkuat koneksi spiritual manusia.
Neuroscience mengungkapkan bagaimana meditasi dapat mengubah struktur otak, menciptakan ketenangan dan empati yang lebih mendalam.
Psikologi positif menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pencapaian material, tetapi dalam pengalaman spiritual dan hubungan yang bermakna.
Melalui pendekatan ilmiah ini, buku ini menghubungkan nilai-nilai spiritualitas dengan bukti nyata menunjukkan bahwa, keduanya saling mendukung, bukan bertentangan.
Dalam Bab 5-7, dieksplor soal Dialog Lintas Iman sebagai Jembatan Harmoni. Fragmentasi sosial di dunia modern sering kali didorong oleh perbedaan agama dan budaya. Bab-bab ini menawarkan solusi melalui dialog lintas iman.
Dengan mengangkat contoh nyata dari komunitas yang berhasil merayakan keberagaman, buku ini menunjukkan bahwa inti semua tradisi agama adalah kebijaksanaan dan kasih universal.
Bab ini mengundang pembaca untuk melampaui batas-batas dogma, membuka ruang bagi diskusi yang jujur dan penuh cinta.
Spiritualitas lintas iman bukan hanya kebutuhan individual, tetapi juga kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai.
Sedangkan dalam Bab Terakhir, ini soal Manifesto Esoterika Forum Spiritualitas.
Bab terakhir adalah sebuah ajakan untuk bertindak.
Buku ini berkisah soal pembentukan Esoterika Forum Spiritualitas, ruang lintas agama, budaya, dan sains yang mengatasi fragmentasi zaman.
Forum ini dirancang untuk menjadi tempat di mana manusia dapat berbagi kebijaksanaan, menyelaraskan teknologi dengan nilai-nilai spiritual, dan membangun komunitas global yang berlandaskan cinta dan empati.
Esoterika, Forum Spiritualitas ini melangkah lebih maju merayakan hari besar aneka agama secara lintas iman, tapi hanya dari sisi sosialnya, tidak ritusnya. Forum ini merayakan hari besar Bahai, Brahma Kumaris, Ahamdiyah, Syiah, KhongHuChu, Budha, Islam, Kristen, Katolik, Agama Leluhur, dan sebagainya.
Sebanyak 4200 agama yang kini hadir dianggap bukan hanya milik penganutnya, tapi warisan kultural milik kita bersama. Pesan-pesan agungnya perlu diuniversalisasi agar juga bisa dinikmati oleh yang bukan penganut resminya.
Manifesto ini menekankan bahwa, spiritualitas di era AI tidak hanya tentang menjaga tradisi, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih manusiawi.
Dengan cinta dan kebijaksanaan sebagai panduan, forum ini adalah jawaban atas tantangan zaman modern, sekaligus pintu menuju harmoni global.
Mengapa Membawa Spirit Para Sufi Penting di Era AI?
Spirit para sufi mengajarkan kita untuk mencari makna di balik segala kesibukan modern. Di tengah materialisme yang mendominasi, cinta menjadi penyeimbang.
Dalam hubungan digital yang dangkal, para sufi mengingatkan kita untuk membangun koneksi sejati. Dan di tengah tekanan hidup, spirit mereka membawa keheningan dan refleksi.
Pesan cinta dan compassion juga ditemukan di tradisi lain.
Dalam agama Kristen, misalnya, tergambar dalam sabda Yesus Kristus (Nabi Isa dalam Islam): Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri.”
Ajakan Yesus Kristus ini, tercatat dalam Matius 22:39, adalah inti dari ajaran kasih yang transformatif.
Kalimat sederhana ini menembus batas agama, budaya, dan zaman. Ia memanggil manusia untuk melihat sesama bukan sebagai “orang lain,” tetapi sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri.
Dalam pandangan ini, kasih bukan hanya tentang memberi; ia adalah pengakuan mendalam bahwa manusia saling terhubung.
Di tengah dunia modern yang terfragmentasi, pesan ini memiliki makna baru. Ketika polarisasi sosial semakin tajam dan teknologi menciptakan jarak emosional, kasih menjadi perekat yang mendasar.
Yesus tidak hanya meminta kita untuk memberi kepada sesama, tetapi juga mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri, melihat mereka dengan empati, menerima kekurangan, dan merayakan keunikannya.
Pesan ini tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga sosial. Dalam dunia yang penuh ketegangan, dari konflik politik hingga ketimpangan ekonomi, kasih dapat menjadi dasar untuk dialog, rekonsiliasi, dan solidaritas.
Dengan mencintai sesama, kita tidak hanya menyembuhkan mereka, tetapi juga menyembuhkan diri sendiri.
Dalam tradisi lain, Bhagavad Gita juga mengajarkan bahwa Cinta Universal adalah Bentuk Tertinggi Dharma.
Bhagavad Gita menempatkan cinta universal sebagai inti dari dharma, kewajiban moral dan spiritual yang menjadi pedoman hidup.
Dalam kitab suci ini, Krishna mengajarkan bahwa manusia mencapai kebebasan sejati melalui pelayanan tanpa pamrih kepada semua makhluk hidup. Cinta universal bukan hanya emosi, tetapi jalan hidup yang melampaui ego dan kepentingan pribadi.
Dalam konteks modern, pesan ini mengajarkan kita untuk melampaui batas-batas sosial, agama, dan nasionalisme.
Cinta universal adalah pengakuan bahwa semua kehidupan saling terkait. Ketika seseorang mencintai tanpa diskriminasi, ia tidak hanya menjalankan dharma, tetapi juga menciptakan harmoni dengan alam semesta.
Dunia yang semakin global membutuhkan cinta universal ini. Ketika manusia menghadapi tantangan seperti krisis iklim, ketimpangan sosial, dan konflik lintas budaya, ajaran Gita menjadi panduan.
Melalui cinta tanpa pamrih, kita belajar untuk melayani orang lain, menjaga keseimbangan alam, dan hidup dalam harmoni dengan seluruh ciptaan.
Juga hal sama diajarkan dalam Karuna (Welas Asih) dalam Buddhisme: Empati Sebagai Jalan Pencerahan.
Karuna, atau welas asih, adalah inti ajaran Buddha. Ia bukan sekadar rasa kasihan terhadap penderitaan orang lain, tetapi dorongan aktif untuk meringankan penderitaan tersebut.
Welas asih adalah bentuk tertinggi dari empati, karena melibatkan pemahaman mendalam terhadap kondisi orang lain dan tindakan nyata untuk membantu mereka.
Dalam dunia modern, Karuna menjadi sangat penting. Ketika masyarakat semakin terisolasi secara emosional oleh teknologi dan individualisme, welas asih menawarkan jalan keluar.
Ia mengajarkan manusia untuk berhenti, mendengarkan, dan hadir bagi orang lain. Lebih dari itu, welas asih juga menyembuhkan diri sendiri, karena membantu orang lain adalah bentuk kebahagiaan sejati.
Ajaran ini juga selaras dengan tantangan global saat ini. Ketika jutaan orang menderita akibat kemiskinan, bencana, dan konflik, Karuna menginspirasi tindakan kolektif yang membawa perubahan.
Welas asih bukan hanya jalan menuju pencerahan individual, tetapi juga kunci untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.
Ren dalam Khonghucu juga membawa spirit yang sama: Kemanusiaan Sebagai Fondasi Masyarakat.
Ren adalah konsep mendalam dalam filsafat Khonghucu yang berarti kemanusiaan atau cinta kasih. Dalam pandangan Khonghucu, Ren adalah inti dari hubungan sosial yang harmonis.
Ia bukan hanya tentang mencintai orang lain, tetapi juga memahami bahwa cinta adalah dasar dari keberlangsungan masyarakat.
Ketika manusia menunjukkan Ren, mereka tidak hanya menjaga hubungan pribadi, tetapi juga memperkuat tatanan sosial.
Di era modern, Ren adalah pengingat akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan di tengah dunia yang semakin terpolarisasi. Ketika masyarakat terpecah oleh perbedaan politik, budaya, atau agama, cinta kasih menjadi jalan untuk menyatukan.
Khonghucu mengajarkan bahwa masyarakat yang kuat adalah yang dibangun di atas hubungan yang penuh kasih, saling menghormati, dan keadilan.
Dalam konteks global, Ren juga relevan untuk menciptakan dialog lintas budaya. Ia mengingatkan bahwa manusia, terlepas dari perbedaan mereka, memiliki kebutuhan dasar yang sama: untuk dicintai, dihormati, dan diakui.
Dengan menerapkan Ren, dunia dapat mencapai harmoni yang melampaui batas-batas fisik dan ideologis.
Teknologi dan Ilusi Makna
Di era dominasi teknologi, khususnya media sosial, manusia menghadapi paradoks yang mencolok: semakin banyak informasi, semakin sedikit pemahaman; semakin terhubung secara digital, semakin terputus secara emosional.
Media sosial, sebagai contoh, telah menjadi panggung yang menampilkan versi terbaik dari kehidupan orang lain. Gambar-gambar liburan mewah, pencapaian karier, atau momen bahagia keluarga sering kali menciptakan ilusi bahwa hidup orang lain sempurna.
Namun, di balik layar, kenyataan sering kali jauh dari gambaran tersebut. Penelitian dari Harvard Business Review (2023) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan rasa iri dan ketidakpuasan diri.
Algoritma media sosial dirancang untuk memperkuat keterlibatan, tetapi sering kali memperparah perasaan tidak berharga dan isolasi. Dalam proses ini, teknologi menciptakan ilusi makna yang dangkal, menggantikan hubungan sejati dengan pengakuan digital yang sementara.
Makna sejati tidak ditemukan di layar ponsel, tetapi dalam hubungan yang nyata dengan sesama, alam, dan Tuhan. Hubungan ini tidak dibangun dari angka like atau followers, melainkan dari keintiman emosional, kasih sayang, dan saling peduli.
Untuk melawan ilusi ini, manusia harus kembali kepada esensi spiritualitas. Refleksi, doa, atau meditasi lintas tradisi menjadi kunci untuk menemukan kedalaman di tengah kebisingan digital.
Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan menghindari jebakan ilusi, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih otentik, penuh makna, dan harmonis.
Teknologi seharusnya menjadi alat untuk mendukung kemanusiaan, bukan menggantikan esensinya.
“Cinta adalah jembatan antara dirimu dan segala hal.”
- Jalaluddin Rumi
Di era AI, cinta tetap menjadi esensi hidup manusia. Ia adalah cahaya di tengah gelapnya data, jembatan di tengah jurang teknologi, dan keheningan di tengah kebisingan dunia.
Membawa spirit para sufi ke era ini adalah tugas kita, karena di dalamnya, kita menemukan jalan pulang menuju kemanusiaan.
*Penulis adalah Konsultan Politik, Founder LSI-Denny JA, Penggagas Puisi Esai, Sastrawan, Ketua Umum Satupena, dan Penulis Buku.