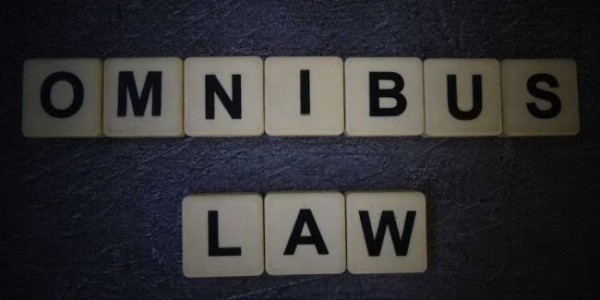telusur.co.id - Puluhan akademisi dan aktivis menolak pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Hal itu dituangkan dalam ‘Manifesto Kewargaan Republik’ yang disampaikan secara daring.
Sedikitnya 77 aktivis dan akademisi lintas universitas yang tergabung dalam komunitas ‘Masker’ menilai Omnibus Law mengabaikan dan makin menghancurkan semangat kewargaan dan berpotensi merobohkan bangunan besar negara Indonesia.
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Joash Tapiheru menyebut, prinsip warga negara sebagai fondasi republik ini kembali dihantam dengan terbitnya sebuah Undang-Undang yang proses formulasinya jauh dari kata transparan.
Menurutnya, republik dibangun di atas etika yang mengakui bahwa, negara dan warga negara sama-sama tidak layak untuk mendaku sebagai perwakilan paling utuh dari negara.
“Namun negara dalam kasus UU Cipta Karya dan konteks besar pandemi ini, etika tersebut kembali dikesampingkan,” beber pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini. Seperti yang dilansir gatra.com. Jumat, (09/10/2020)
Joash menjelaskan, penolakan pada UU Cipta Karya adalah wujud komitmen sebagai warga negara Republik Indonesia.
"Sebagai warga negara yang berdaulat, aktif secara politik, dan setara kami menolak diposisikan sekedar sebagai objek pasif yang hanya perlu membungkuk menerima ‘bantuan kebaikan hati negara’, karena itu bukan bantuan tetapi kewajiban negara memenuhi hak warga negaranya,” paparnya
Joash mengatakan, penolakan dan gugatan pada UU Cipta Karya adalah ekspresi upaya warga negara untuk menjaga etika republik demi kelangsungan negara dan bangsa.
Dalam etika republik, ia menjelaskan, pemimpin dan pejabat negara adalah primus inter parres, yang pertama di antara yang setara.
"Bukan sosok ‘orang tua’ yang selalu lebih tahu dan lebih bijak dari yang lain. Kita sama-sama tuan dan puan di republik ini,” lugas Joash.
Manifesto Kewargaan Republik (Masker) dari puluhan akademisi ini menyatakan UU Cipta Kerja mengabaikan posisi warga sebagai pusat segenap pertimbangan, melainkan mengedepankan kepentingan pemodal dan investor.
Ironisnya, penghancuran terhadap fondasi demokrasi berbasis hak-hak kewargaan tadi dilakukan ketika kita tengah bertarung menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Ini merupakan bentuk pengkhianatan brutal oleh para elit penguasa.
Alih-alih menjalankan perannya mendorong regulasi yang mengendepankan keselamatan dan melindungi warga negara, lembaga eksekutif dan legislatif justru melakukan kesepakatan anti-demokratik yang melampaui batas-batas etika bernegara.
Komunitas akademisi Masker menyebut pemerintah membajak institusi demokrasi untuk meloloskan legislasi yang akan memperluas akumulasi modal tanpa mengindahkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, seraya memperkosa tanah air Indonesia.
“Omnibus Law membalikkan arah reformasi dengan cara mengembalikan sentralisme kekuasaan ala Orde Baru; melucuti peran daerah dan menarik berbagai macam bentuk perizinan ke pusat,” lanjut manifesto itu.
Omnibus Law potensial memicu kekerasan berskala besar ketika regulasi tidak mempertimbangkan aspirasi dan partisipasi warga. Ketika partisipasi absen, kelestarian tanah air dan bumi Indonesia hanya akan mengandalkan alat-alat kekerasan negara, seperti polisi dan tentara, yang akan memperparah konflik dan pelanggaran HAM.
“Atas dasar itu komunitas akademisi Masker menolak UU Cipta Kerja dan mendukung semua upaya elemen demokratis baik berupa judicial review maupun segala bentuk pernyataan pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi dan menentang seluruh upaya represif berupa pelanggaran HAM dan penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE,” demikian manifesto tersebut.
Perlu diketahui, nama-nama yang tergabung di Masker antara lain dosen Universitas Airlangga Airlangga Pribadi Kusman, pengajar hukum UGM Agung Wardhana, dosen UKSW Putri Hergianasari, dan jurnalis senior Farid Gaban (her)