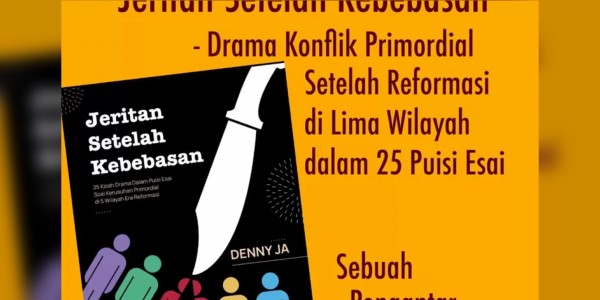Telusur.co.id - Oleh : Denny JA
“Mayat-mayat ditumpuk, di kiri dan kanan. Semuanya mayat. Sepanjang jalan bau amis. Ada yang dibakar. Ada mayat yang membengkak, sepanjang jalan.”
Ini bukan adegan film. Ini kesaksian Ronald. Ketika konflik Maluku, penganut Islam versus penganut Kristen, di tahun 2000, usia Ronald masih 10 tahun.
Ia ceritakan pengalamannya itu kepada BBC (1). Walau masih bocah, ia diajak komunitasnya untuk ikut perang bela agama. Prinsipnya membunuh atau dibunuh.
Konflik Maluku yang berlangsung sejak 1999-2002 telah menelan 8.000-9.000 nyawa.
Ini Maluku, tanah yang melahirkan lagu-lagu lembut dan jenaka, seperti lagu Ayo Mama:
“Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma, cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa.”
Di Maluku yang sama, di satu masa, 1999-2002, pernah menjadi Maluku yang gila. Mereka saling membunuh dengan basis agama. Mereka menciptakan Laskar Kristus versus Laskar Jihad yang saling memusnahkan.
Itu cuplikan satu wilayah di masa awal kebebasan politik di Indonesia setelah tahun 1998. Tak hanya di Maluku, di empat wilayah Indonesia lainnya, pasca dan menjelang reformasi, nyaring terdengar “Jeritan Setelah Kebebasan.”
Lebih dari 100 kepala manusia dipancung dalam konflik di Sampit, Kalimantan Tengah 2001, antara suku Dayak versus suku Madura. Puluhan kepala manusia itu di arak di jalan-jalan, dijadikan ritus dan simbol kemenangan.
Lebih dari 400 orang hangus terbakar atau dibakar di dalam mall dalam kerusuhan rasial di Jakarta di tahun 1998. Banyak mayat itu tak lagi dikenali. Mereka terjebak dalam mall yang disiram minyak tanah dan pintu keluarnya dinyalakan api.
Lebih dari 18 tahun, penganut Ahmadiyah hidup di pengungsian, terusir dari tanahnya sendiri, tempat kelahirannya yang mereka miliki turun-temurun di Mataram, NTB sejak tahun 2006.
Anak-anak itu tak tahu apa-apa. Mereka dilahirkan dari orang tua yang sudah memeluk Ahmadiyah. Mereka ikut diusir hanya karena keyakinan itu.
Lebih dari 1.700 etnik Bali diungsikan dari desanya di Lampung. Puluhan rumah mereka dibakar dalam konflik etnik Bali vs Lampung di tahun 2012.
Seorang kakek itu tak mengerti apa yang terjadi. Ia tak bisa lagi berlari seperti anak muda lain. Ia mencoba berjalan cepat. Tapi ia mudah dikejar dan dibunuh. Itu semata karena ia orang Bali.
Aneka kisah di atas terlalu kelam untuk dikenang, namun terlalu penting untuk dilupakan. Bagaimana kita bisa mengolah peristiwa itu menjadi pelajaran berharga?
Puisi esai menjadi cara bertutur baru mendokumentasikan kisah True Story itu. Namun berbeda dengan penulisan sejarah atau jurnalisme, puisi esai menambahkan drama dan fiksi.
Mengapa diperlukan fiksi untuk mengkisahkan true story? Sepotong sejarah akan lebih mudah diingat, lebih menyentuh jika dikisahkan melalui drama yang menyentuh.
Pembaca sepenuhnya akan paham. Bahwa setting sosial dalam puisi esai itu memang fakta yang terjadi di panggung sejarah. Tapi drama dalam setting faktual itu semata tambahan imajinasi.
Puisi esai bisa dikatakan versi lain dari historical fiction yang sudah memiliki jejak yang panjang dalam tradisi sastra. Bedanya, sejarah dalam terminologi historical fiction itu untuk kisah yang sudah terjadi lebih dari 50 tahun lalu.
Puisi esai tidak membatasi periode waktu. Apapun yang sudah terjadi, bahkan kasus yang kini masih berlangsung dapat menjadi ibu kandung bagi karya puisi esai.
Buku ini memang dimaksudkan merekam 25 kisah drama yang difiksikan dari 25 kisah nyata dalam konflik primordial paling keras pasca reformasi.
Yayasan Denny JA untuk Indonesia Tanpa Diskriminasi melakukan riset di tahun 2012. Ini temuannya. (2)
Dari tahun 1998-2011, selama 14 tahun, terjadi 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi di Indonesia.
Kasus kekerasan ini bisa dipilah dalam lima jenis konflik primordial. Sebanyak 65 persen konflik itu berlatar agama/paham agama.
Sebanyak 20 persen kekerasan berdasarkan etnik. Sebesar 10 persen kekerasan berdasarkan gender. Sebesar 5 persen kekerasan bersandarkan orientasi seksual.
Ini yang unik soal jenis konflik pasca reformasi. Konflik antar masyarakat lebih bersifat priomordial, komunal. Karakter konflik ini berbeda dengan konflik di era Orde Baru, yang lebih berupa diskriminasi dan pertengkaran ideologis.
Dari kasus diskriminasi yang terjadi, Yayasan Denny JA mendata lima kasus terburuk di lima wilayah.
Adapun indikator yang digunakan dalam riset itu cukup terukur. Yaitu jumlah korban yang tewas, luas konflik yang terjadi, lama konflik, kerugian materi, dan frekuensi berita.
Setiap variabel diberikan nilai 1-5. Dalam penyusunan ranking, dibuat indeks dengan pembobotan.
Skor 50 diberikan pada variabel jumlah korban. Nilai 40 untuk lamanya konflik. Angka 30 untuk luas konflik. Skor 20 untuk kerugian materi. Terakhir angka 10 untuk frekuensi berita.
Ini tabel lima konflik primordial dan komunal di Indonesia paska reformasi. Konflik Ambon berada di posisi teratas, dengan nilai 750. Di tempat kedua: konflik Sampit dengan nilai 520.
Ranking ketiga: kerusuhan Mei 1998, dengan total skor 490. Selanjutnya: kasus pengungsi Ahmadiyah di Mataram (470). Terakhir konflik Lampung Selatan antara suku Lampung dan Bali (330). Total dari lima konflik terburuk ini telah menghilangkan nyawa 10.000 warga negara Indonesia. Yayasan Denny JA juga mencatat data yang lebih detail. Konflik Maluku menelan korban terbanyak: 8.000-9.000 orang meninggal dunia.
Konflik itu juga menyebabkan kerugian materi 29.000 rumah terbakar, 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank hancur.
Rentang konflik yang terjadi juga yang paling lama, yakni sampai 4 tahun. Sementara konflik Sampit yang berlatar belakang etnis, antara Dayak dan Madura, menyebabkan 469 orang meninggal dunia dan 108.000 orang mengungsi. Rentang konfliknya pun mencapai 10 hari.
Sedangkan kerusuhan di Jakarta yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 juga tidak kalah mengerikan. Konflik ini menelan korban 1.217 orang meninggal dunia, 85 orang diperkosa, dan 70.000 pengungsi.
Walau hanya berlangsung tiga hari, kerugian materi yang ditimbulkan oleh kerusuhan Mei 1998 mencapai Rp 2,5 triliun. Konflik Ahmadiyah di Transito Mataram telah menyebabkan 9 orang meninggal dunia, 8 orang luka-luka, 9 orang gangguan jiwa. Sebanyak 9 orang dipaksa cerai, 379 terusir, 3 orang keguguran, 61 orang putus sekolah.
Juga terdapat 45 orang dipersulit mengurus KTP dan 322 orang dipaksa keluar Ahmadiyah.
Meski tidak menimbulkan korban jiwa yang besar, konflik ini menjadi kaca melihat wajah Indonesia. Setelah puluhan tahun merdeka, warga negara menjadi pengungsi di negaranya sendiri.
Peristiwa ini mendapat perhatian publik cukup luas. Ia juga memperoleh perhatian media cukup kuat dan rentang peristiwa pasca konflik yang panjang.
Bahkan hingga pengantar ini ditulis di tahun 2022, sebagian warga Ahmadiyah itu tetap tak bisa kembali ke tanah tempat mereka dilahirkan. Itu hanya karena mereka meyakini paham agamanya.
Lain lagi kasus yang terjadi di Maluku, konflik kekerasan di Lampung Selatan menimbulkan kematian sebanyak 14 orang. Juga menyebabkan lebih dari 1.700 orang mengungsi.
Secara keseluruhan, negara terlihat seolah mengabaikan konflik yang sudah membuahkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam beberapa kasus bahkan tidak ada pelaku atau otak pelaku kekerasan yang diusut.
Bulan September 2022, di Sabah, Malaysia, diselenggarakan Festival Puisi Esai Antar Bangsa. Pemerintahan setempat ikut membiayai festival ini.
Sepuluh tahun sejak saya menulis buku puisi esai pertama: Atas Nama Cinta (2012), tak terasa puisi esai ini sudah berjalan cukup jauh, hingga melampaui batas negara Indonesia.
Di samping sudah mencetak 150 buku dan video puisi esai, sebagian dalam bahasa Inggris, komunitas puisi esai juga sudah membentuk ikatan puisi esai ASEAN.
Dalam orasi melalui video menyambut festival puisi esai antar bangsa, saya menyampaikan riset yang dimuat Washington Post: Poetry is Going Extinct. Puisi menjadi mahluk langka. (3)
Puisi dalam bentuknya yang sekarang semakin ditingggalkan, tidak dibaca. Dari berbagai bentuk kesenian dan sastra, puisi ada di ranking kedua terbawah setelah opera yang semakin tak dilihat.
Puisi esai menjadi salah satu ijtihad budaya. Ia ikhtiar untuk kembali membawa puisi ke tengah gelanggang.
Buku ini, Jeritan Setelah Kebebasan, dibuat untuk lebih memperkenalkan puisi esai kepada publik luas. Setiap tahun di bulan Desember akan diselenggarakan festival menulis puisi esai.
Publik luas diundang untuk mengisahkan aneka isu di lingkungannya yang berhubungan dengan problem hak asasi manusia, diskriminasi, untuk diekspresikan, diceritakan Kembali (retelling) melalui puisi esai.
Buku ini yang mengangkat 25 kisah sebenarnya, yang difiksikan dalam 25 puisi esai akan menjadi rujukan.
Isu yang menjadi magnet dalam masyarakat, true story, digemakan kembali melalui puisi esai, agar menjadi lessons to learn. Yang bukan penyair diundang untuk ambil bagian.
Mengapa kita percaya kekuatan puisi, kekuatan kata? Sebuah pepatah menyatakan:
“Kata-kata lebih kuat daripada senjata dan parang, karena kata-kata menembus lebih dalam dan melukai lebih tajam.”
Pepatah ini mungkin saja hanya kiasan dan hiperbolis. Tapi melalui kata, pesan yang kuat, memang mampu menyelinap, menyentuh sampai ke hati.
CATATAN
(1) Saling bunuh di Maluku.
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43207033
(2) Lima wilayah paling keras terjadi konflik primordial pasca reformasi.
https://amp.kompas.com/tekno/read/2012/12/23/15154962/nasional
(3) Puisi yang ada sekarang, jika tidak berinovasi akan semakin ditinggalkan.
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/04/24/poetry-is-going-extinct-government-data-show/
*Penulis adalah Konsultan Politik, Founder LSI-Denny JA, Penggagas Puisi Esai, Sastrawan, dan Penulis Buku.