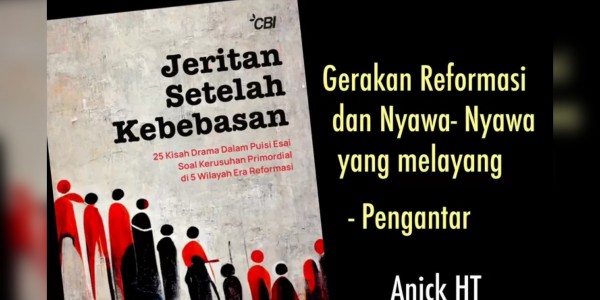Telusur.co.id - Pengantar Editor : Anick HT
Gerakan reformasi adalah momentum penting perjalanan peradaban bangsa dari era otoritarianisme yang serba gelap menuju era demokrasi yang menjanjikan harapan perubahan ke arah yang lebih memanusiakan warganya.
Namun, momen gerakan reformasi tak hanya berisi kisah kepahlawanan para mahasiswa pejuang. Ia juga menjadi titik sejarah yang memunculkan betoro kolo dan meruyak hidup dan kehidupan banyak orang, merenggut banyak nyawa.
Tak bisa dibayangkan, seperti yang disebut dalam hasil riset Yayasan Denny JA untuk Indonesia tanpa Diskriminasi, dari tahun 1998-2011, selama 14 tahun, terjadi 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi di Indonesia.
Mungkin sebagian besar kasus itu terkubur oleh waktu, dan tak dialami langsung oleh generasi dominan saat ini. Sebagian tanpa penyelesaian tuntas dan menggantungkan misteri. Sebagian lain masih menyisakan trauma berkepanjangan. Sebagian lain bahkan masih terjadi dan menjadi pilihan cara menyelesaikan masalah di antara sesama.
Denny JA merekam lima jenis konflik dan kerusuhan yang dianggap paling krusial dalam perjalanan era reformasi, yakni: Kerusuhan Rasial Jakarta, Mei 1998; Kerusuhan Sampit 2001, Suku Dayak Versus Suku Madura; Konflik Etnis Lampung VS Etnis Bali, 2012; Kasus Ahmadiyah di NTB, 2006-2022; dan Konflik Maluku, 1999-2002 Rekaman ini berupada 25 kisah dramatik yang ditulis dalam bentuk puisi esai, Jeritan Setelah Kebebasan.
Lima jenis konflik dan kerusuhan yang menandai salah satu puncak terbawah sejarah Indonesia itu nampak sangat menyakitkan, bahkan untuk sekadar diceritakan kepada anak cucu.
Ichsan Malik, seorang fasilitator perdamaian yang terlibat langsung dalam berbagai konflik, bahkan menuturkan, setelah membaca buku Jeritan Setelah Kebebasan ini, sontak bereaksi: “…mulut agak terasa pahit, dada terasa agak sesak, dan kepala agak berdenyut-denyut.” (Kedamaian Setelah Jeritan dan Kebebasan).
Lalu mengapa Denny JA mengangkatnya menjadi tema dari 25 puisi esai yang dibukukan dalam Jeritan Setelah Kebebasan? Mengapa kisah tragis dan penuh kengerian ini harus diangkat lagi ke permukaan?
Denny JA memiliki jawabannya sendiri. Baginya, kisah-kisah yang telah mengorbankan lebih dari 10.000 nyawa manusia Indonesia itu terlalu kelam untuk dikenang, namun terlalu penting untuk dilupakan.
Yang terpenting adalah, bagaimana kita bisa mengolah peristiwa itu menjadi pelajaran berharga?
Ia menolak lupa. Menolak menganggap bahwa peristiwa-peristiwa mengerikan itu tak pernah terjadi di bumi indah ini. Menolak untuk mengabaikan bahwa kemajuan peradaban kita hari ini tak lepas dari pengorbanan nyawa-nyawa itu.
Baginya, melupakan berbagai tragedi itu berarti membuang peluang untuk mengambil pelajaran berharga bagi peradaban bangsa ini. Menutupi sejarah kelam berarti justru menyia-nyiakan pengorbanan mereka-mereka yang tak seharusnya kehilangan nyawa.
Tak ada alasan apa pun yang bisa dijadikan dasar penghilangan nyawa manusia. Karena itu, tak ada alasan pula untuk tidak mengambil pelajaran dari nyawa-nyawa yang hilang tersebut.
Bagaimana Denny JA mengemasnya menjadi pelajaran bagi kita? Ia memiliki senjata penting bernama puisi esai. Seperti disebutnya, puisi esai menjadi cara bertutur baru dalam mendokumentasikan kisah true story itu.
Fakta-fakta mengerikan itu. Berbeda dengan penulisan sejarah atau jurnalisme, puisi esai menambahkan drama dan fiksi. Gabungan dari olah fakta dan fiksi dramatik memungkinkannya menyajikan catatan sejarah dan sekaligus menghadirkan narasi pembelajaran penting dari sejarah tersebut.
Mengapa diperlukan fiksi untuk mengisahkan true story? Bagi Denny, sepotong sejarah akan lebih mudah diingat, lebih menyentuh jika dikisahkan melalui drama yang menyentuh.
Racikan inilah yang menurut Isbedy Stiawan ZS menjadi kekuatan buku ini. Denny JA “seperti memiliki '100 mata' untuk melihat, mengamati, sekaligus menentukan sudut yang pas untuk menulis kisah-kisah dramatik tersebut.” ('Konflik Balinuraga' dalam Puisi Esai Denny JA).
Konflik dan kerusuhan itu adalah pengalaman traumatik, bukan hanya bagi korban, namun juga bagi aktor dan pelaku. Setelah sekian lama berjarak dengan peristiwanya, setelah terbangun kesadaran kolektif bahwa konflik tak menghasilkan apa-apa selain kehancuran, banyak pelaku yang kemudian justru tersiksa, dihantui rasa bersalah berkepanjangan.
Inilah yang disebut oleh Jacky Manuputty dalam buku ini sebagai titik balik. “Syair-syair Denny JA menawarkan pendekatan yang utuh dengan memotret proses transformasi aktor dari konflik ke perdamaian. Kisah-kisah titik balik adalah bentuk narasi damai yang inspiratif, memiliki dampak dan daya tarik yang sama dengan drama konflik.” (Biarlah Rebana dan Totobuang Kembali Bersanding).
Dalam jarak waktu yang cukup jauh sekarang ini, kita pelan-pelan menyadari bahwa para korban di era reformasi itu tidak tahu apa yang membuat mereka dibunuh, diperkosa.
Apa yang menyebabkan rumah-rumah mereka dirusak tanpa belas kasihan. Tak ada satupun alasan yang bisa diterima akal mengapa di negeri yang damai ini, kemarahan dan kebencian bisa tiba-tiba merasuki manusia-manusia beradab.
Begitu juga dengan para aktor dan pelaku yang merusak, memperkosa, dan membunuh sesamanya. Banyak dari mereka tidak benar-benar menyadari atas alasan apa mereka melakukan itu semua.
Atas dasar apa mereka memiliki kewenangan untuk menghilangkan nyawa manusia lain.
Buku di hadapan Anda ini adalah kumpulan tanggapan langsung terhadap 25 kisah dramatik dalam bentuk puisi esai yang ditulis oleh Denny JA.
Para penulis buku ini merepresentasikan berbagai sudut pandang yang diharapkan memperkaya pembaca, yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dengan konflik dan kerusuhan yang dialami bangsa ini.
Mengutip Anis Hidayah dalam buku ini (Luka yang Terus Menganga), “Buku ini bukan sekadar karya sastra. Ketika sejarawan tak mampu mengeja peristiwa kelam pelanggaran HAM, buku ini hadir sebagai referensi untuk mengisi rumpang sejarah yang pernah terjadi. Sehingga buku ini penting untuk dibaca, terutama generasi muda yang lahir pasca 1998.
Kisah-kisah yang ada dalam buku esai puisi dengan latar 5 tragedi pelanggaran HAM di Indonesia ini ditulis seakan bernyawa. Pesan-pesan tentang impunitas, trauma para korban, dan lemahnya perlindungan negara sangat kuat dalam buku ini.“
Buku ini sekaligus adalah upaya kecil untuk merawat memori, lalu mengambil pelajaran berharga dari apa pun yang telah mewarnai perjalanan bangsa yang besar ini. Bahwa nyawa-nyawa yang telah melayang itu tak boleh menjadi sia-sia.